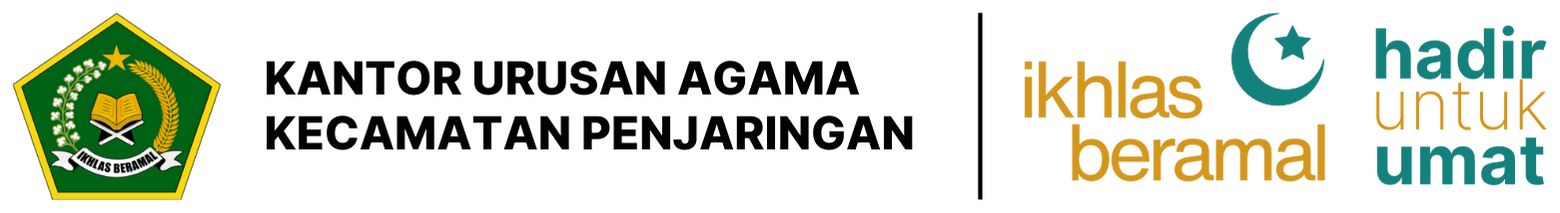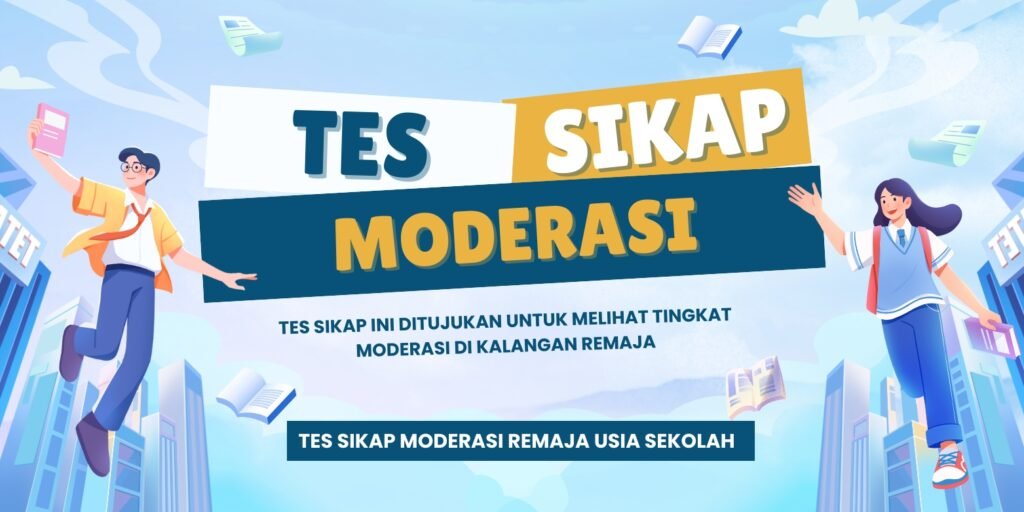Suara tahlil di malam Kamis, tembang syair maulid di bulan Rabiul Awal, atau upacara selametan menjelang panen, adalah sedikit dari banyak tradisi yang perlahan memudar. Tradisi yang dulu menjadi denyut spiritual dan sosial masyarakat kini sering dianggap usang, bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri. Sebagian menyebutnya “tidak murni”, sebagian lagi “tidak relevan”. Namun jika menelusuri sejarah Islam di Nusantara, kita akan menemukan bahwa justru tradisi itulah yang menjadi jembatan antara Islam dan masyarakat. Para wali dan ulama terdahulu tidak menghapus budaya, tetapi menuntunnya agar bernafas dalam nilai-nilai tauhid. Di tangan mereka, budaya menjadi jalan dakwah, bukan penghalang, apalagi menyesatkan iman.
Islam datang bukan sebagai agama yang menghapus dan mengikis akar budaya, tetapi sebagai ajaran yang menanam nilai-nilai baru di dalam tanah kebudayaan itu sendiri. Prinsip al-Muhafazhah ‘alal Qadimish Shalih wal Akhdu bil Jadidil Ashlah (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik) mengajarkan kita untuk menjaga tradisi lama yang baik sekaligus merangkul hal-hal baru yang membawa kebaikan yang lebih besar.
Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ḥujurat :13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku “agar saling mengenal”, bukan saling meniadakan. Islam mengakui keberagaman sosial dan budaya sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, sebuah sunnatullah yang tidak bisa dihapus dengan fatwa tunggal. Pendekatan dakwah para wali di masa awal Islamisasi Jawa adalah bukti paling kuat bahwa Islam dapat hidup bersama budaya tanpa kehilangan kesuciannya. Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang dan tembang Jawa, Sunan Kudus membangun masjid dengan arsitektur Majapahit, sementara Sunan Bonang memperkenalkan gamelan sebagai media dakwah.
Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Alshehaby (2020) di International Journal of Cultural Property, yang menemukan bahwa pelestarian budaya dalam Islam memiliki dasar etik yang kuat. Islam memandang pelindungan budaya sebagai bagian dari “hak atas perkembangan manusia” (right to development) bukan sekadar urusan estetika atau nostalgia masa lalu. Di Indonesia, model ini berlanjut dalam pendidikan Islam. Studi oleh Najib Aulia Rahman (2023) menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya di tengah modernisasi. Nilai-nilai seperti hormat kepada guru, gotong royong, dan cinta tanah air menjadi bentuk nyata dari “tradisi luhur” yang bersenyawa dengan ajaran Islam.

Antara Puritanisme dan Globalisasi
Namun kini muncul tantangan baru, seakan seperti dua kutub ekstrem yang sama-sama mengancam keberlanjutan. Di satu sisi, ada pandangan puritan yang menilai setiap bentuk tradisi lokal sebagai penyimpangan dari tauhid. Di sisi lain, globalisasi melahirkan budaya pop yang mengikis akar lokal melalui media dan gaya hidup. Berdasarkan hasil penelitian dalam Mimbar: Journal of Social and Islamic Studies (UIN Jakarta, 2022) menemukan pola global: komunitas Muslim di berbagai negara sedang berjuang menyeimbangkan identitas religius dan budaya lokal mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Maroko, Turki, dan Malaysia dimana globalisasi budaya sering menggeser ritual dan simbol lokal. Keduanya, baik ekstremisme dan globalisasi, bisa membuat umat kehilangan arah, dimana yang satu menolak masa lalu, yang lain melupakan masa depan.
Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah
Konsep moderasi beragama (al-wasathiyah) muncul sebagai jalan tengah yang memungkinkan agama dan budaya berjalan beriringan. Islam moderat tidak berarti melemahkan iman, tetapi menegakkan keseimbangan antara teks dan konteks, antara syariat dan realitas sosial. Dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (2020) dijelaskan bahwa pelestarian budaya adalah salah satu bentuk nyata dari prinsip moderasi. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan akidah justru memperkuat ukhuwah sosial, memperdalam spiritualitas, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Inilah sebabnya mengapa praktik seperti tahlilan, selametan, dan maulid Nabi tetap hidup di banyak daerah. Bukan karena fanatisme tradisi, melainkan karena di sana ada nilai keislaman seperti doa, kebersamaan, syukur, dan cinta kasih. Budaya lokal adalah laboratorium tempat Islam menguji kelenturannya. Di sinilah bahasa atau istilah teologi turun ke tanah di antara doa panen, upacara adat, dan gotong royong membangun masjid. Di sini pula konsep rahmatan lil ‘alamin menemukan bentuk sosialnya.
Selain itu peneliti seperti Mohammad Izdiyan Muttaqin (2022) menyebut fenomena ini sebagai “cultural adaptation of Islamic ethics” kemampuan Islam untuk berinteraksi dengan budaya tanpa kehilangan esensi moralnya. Hal ini menjadi penanda keunikan Islam di Asia Tenggara, di mana keberislaman melebur dengan keindonesiaan tanpa konflik identitas. Namun, pendekatan ini menuntut kecerdasan kultural. Tidak semua tradisi bisa diterima mentah-mentah, dan tidak semua modernisasi harus ditolak. Islam mengajarkan prinsip i‘tidal (keseimbangan dan proporsionalitas). Inilah etika berpikir yang memungkinkan umat bersikap bijak terhadap perubahan zaman.
Tradisi bukan sebuah museum, melainkan hidup, tumbuh, dan bisa diperbarui. Prinsip al-muḥafaẓah ‘ala al-qadim al-saliḥ wa al-akhdh bi al-jadid al-aṣlaḥ mengajarkan kita untuk tidak hanya menjaga, tetapi juga berinovasi. Menjaga yang luhur, sambil mencipta yang lebih baik. Ketika masyarakat muslim mampu memahami ini, Islam tidak lagi tampak sebagai agama yang kaku, melainkan agama yang penuh welas asih, yang menghargai warisan leluhur tanpa kehilangan arah ke ilahi. Inilah ciri khas muslim Indonesia, identitas masyarakat yang senantiasa menjaga warisan luhur dengan orisinalitas praktik beragama yang tumbuh di bumi, tapi berakar di langit.