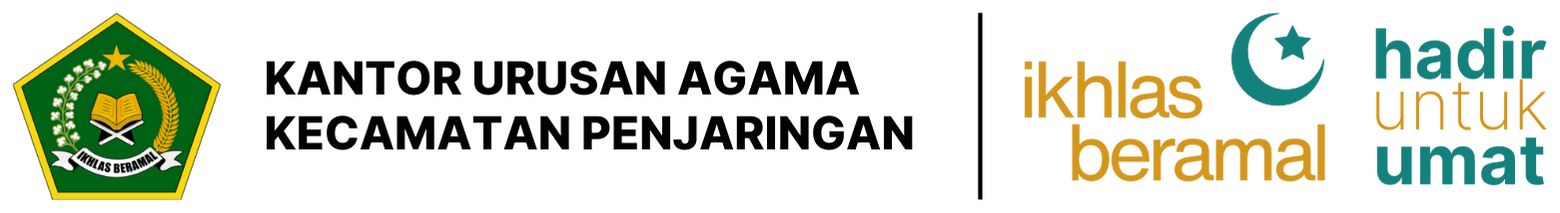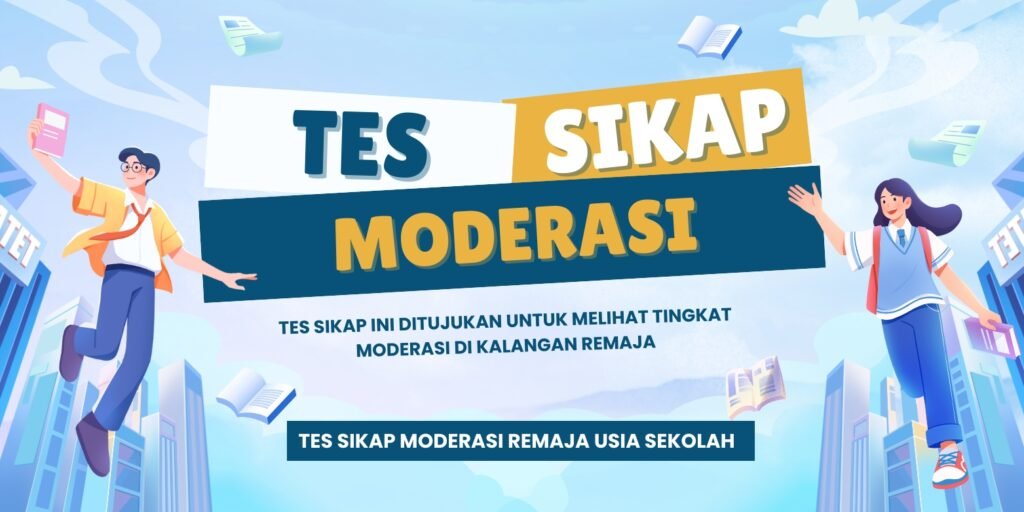Moderasi beragama sering diperlakukan sebagai variabel yang bisa “diukur” dari apa yang tampak di linimasa: frekuensi unggahan toleran, rasio komentar bermuatan kebencian, atau pola retweet narasi ekstrem. Klaim ini kini digunakan sebagai dasar analisis akademik, liputan media, dan bahkan kebijakan mitigasi. Namun, pertanyaan metodologis mendasar tetap: apakah jejak digital itu representatif dan valid sebagai ukuran moderasi beragama? Jawaban praktisnya: tidak selalu dan studi terbaru (2024–2025) menunjukkan baik potensi maupun batasan serius dalam menjadikan medsos sebagai tolok ukur tunggal.
Ruang Publik dan Performativitas
Habermas (1989) berargumen bahwa ruang publik ideal adalah ruang wacana di mana warga bisa berbicara secara rasional, kritis, dan setara mengenai kepentingan bersama. Media sosial menawarkan janji ruang publik baru akses lebih terbuka, dialog tak terbatas pada elite namun kenyataannya seringkali dibelokkan oleh logika algoritme: konten yang emosional, provokatif, atau kontroversial lebih mudah menjaring perhatian. Alhasil, publik menjadi lebih bersuara, tapi tidak selalu lebih rasional.
Goffman (1959) memperlihatkan bahwa kita semua melakukan performance dalam interaksi sosial: kita memilih citra yang ingin ditampilkan, mengatur bagaimana diri kita “dilihat” oleh orang lain. Turkle (1995) menambahkan bahwa identitas daring adalah arena eksperimen: dalam keleliruan anonimitas atau semi-anonimitas, orang dapat mencoba berbagai “versi diri” yang mungkin jauh dari tindakan nyata mereka. Dengan demikian, komentar moderat atau toleran di Facebook atau Twitter bisa jadi bagian dari persona yang ingin dilihat “baik” oleh publik, bukan ekspresi keseharian yang konsisten.
Suler (2004) melalui konsep online disinhibition effect menjelaskan mengapa ujaran daring sering lebih agresif, kasar, atau ekstrem dibanding interaksi tatap muka. Faktor anonim atau jauh secara psikologis, kurangnya penalti langsung, serta absennya ekspresi nonverbal (intonasi, mimik, gestur) membuat batas kesopanan dan empati lebih mudah dilanggar. Ini bisa memperburuk polarisasi dan menjadikan wacana keberagamaan lebih keras daripada praktik moderasi bisa menahan diri dalam dunia nyata.
Implikasi Metodologis: Pengukuran Moderasi Beragama di Ruang Digital
- Gunakan pendekatan campuran (mixed methods):
Kombinasi data kuantitatif digital (misalnya analisis teks media sosial, sentimen, frekuensi ujaran toleran/bertolak belakang) dengan data kualitatif (wawancara, observasi lapangan, studi kasus) agar bisa menangkap bagaimana moderasi dijalankan dalam kehidupan nyata. - Kontekstualisasikan data daring:
Perhatikan siapa yang berbicara, dalam setting apa (publik/privat), identitas mereka, relasi sosial mereka, dan apakah mereka memiliki insentif “performatif” untuk tampil moderat atau agresif. - Validasi melalui aksi nyata:
Misalnya, mengukur keterlibatan dalam kegiatan antaragama, toleransi dalam interaksi langsung, kontribusi dalam komunitas yang plural, keputusan dalam memilih pemimpin atau kebijakan—apakah moderasi sebagai nilai yang diedukasi juga dijalankan? - Kenali bias algoritmik & efek platform:
Algoritme yang mempromosikan engagement sering mengangkat konten yang kontroversial. Peneliti harus sadar bahwa platform membentuk apa yang dilihat dan disebarkan, bukan hanya merefleksikan apa yang “ada”.
Kesimpulan
Moderasi beragama di ruang digital sering membutuhkan tafsir kritis. Ujaran dan ekspresi daring bisa memberi gambaran, tapi bisa juga memberi ilusi. Tanpa metodologi yang hati-hati dan pemahaman teori yang memadai, kita bisa salah mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sudah “moderate” atau “toleran intensif” padahal dalam praktik nyata, sikap dan tindakan bisa berbeda jauh.Moderasi sejati bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang dilakukan ketika kamera dimatikan, jari berhenti mengetik, dan publik digital tak melihat.